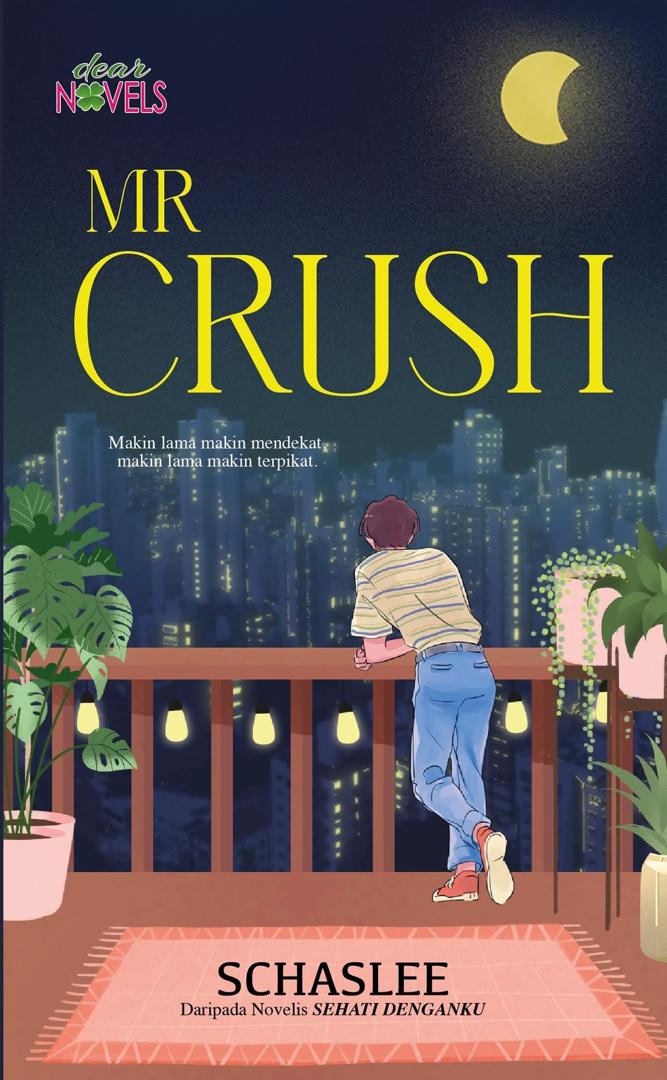AKU menggeliat kecil untuk membetulkan urat saraf. Naik belok pinggang aku kerana menaiki bas dalam perjalanan jarak jauh.
Aku baru saja tiba di daerah kelahiran aku. Hari masih gelap. Bunyi azan subuh baru saja kedengaran. Aku berjalan kaki bersama bagasi, menuju ke surau untuk menunaikan solat.
Sudah lama aku tidak jejakkan kaki di pekan. Kali terakhir semasa aku pulang untuk sambutan hari raya tahun lepas.
Selepas selesai menunaikan solat, aku merenung telefon. Mahu telefon ayah, rasa serba salah pula. Siapa agaknya yang boleh datang jemput aku?
Mata aku terpandang nombor telefon Syakila. Syakila itu sepupu aku. Dia anak pak ngah. Dalam ramai-ramai anak pak ngah, dia saja yang suka duduk di kampung. Syakila juga yang tolong tengokkan nenek. Suka betul dia tinggal di kampung.
Nombornya aku dail. Panggilan pertama hanya kedengaran suara operator menyahut. Aku cuba lagi untuk kali kedua. Lama aku tunggu sebelum panggilan aku disambut.
“Helo, Lea. Ada apa?” Kedengaran suara Syakila di hujung talian.
“Kau buat apa tu? Baru bangun ke?”
“Tak adalah. Aku baru siap solat. Ada apa kau telefon aku ni?”
“Nak minta tolong boleh tak?” Aku bersuara dengan rasa teragak-agak.
Lebih pada segan sebenarnya kerana aku sudah lama tidak menghubunginya. Namun, hubungan kami baik-baik saja.
“Tolong apa? Lekaslah cakap. Aku sakit perut ni. Nature calls.” Suara Syakila sudah berubah irama.
Tergesa-gesa mahu menamatkan panggilan.
“Nanti ambil aku dekat stesen bas dekat pekan, boleh tak?” Aku bersuara malu-malu.
“Boleh, boleh. Bagi aku memerut dulu. Bye.” Panggilan dimatikan begitu saja.
Betul-betul tak tahan nampak gayanya. Aku tergelak kecil.
Syakila, nama saja ayu. Tuan punya badan, sebaliknya. Sebut saja nama Syakila, terus aku terbayang Syakila yang selalu pakai seluar jean besar, T-shirt besar dan tudung sarung. Gayanya selekeh mengalahkan aku.
Aku datang juga rasa mahu bergaya, mahu bersolek. Kalau Syakila, tak kira hari raya ke, majlis kenduri atau apa-apa saja majlis keramaian, selalu pakai baju tak kena gaya. Kadang-kadang kalau dia pakai baju kurung pun, di kaki masih lagi dengan kasut Converse. Maklumlah, jiwa dia rock sikit.
Aku bersandar pada dinding surau. Keadaan sudah sunyi sepi. Matahari juga sudah naik. Menyinari hari dan menyalurkan rasa hangat ke permukaan bumi.
AKU bingkas bangun apabila dengar bunyi kereta. Syakila sudah sampai bersama kereta Kancilnya. Aku panggil kereta itu Kancil turbo. Enjinnya berbunyi kuat. Dari jauh sudah kedengaran.
Orang kampung juga sudah kenal dengan kereta Syakila. Dengar bunyi enjinnya saja sudah tahu.
“Weh, cepatlah masuk. Aku nak pergi pasar pagi pulak ni. Nak beli barang sikit.” Syakila menjerit dari dalam kereta.
Aku geli hati melihat muka tak sabar Syakila.
“Ya, sabarlah, mak cik. Bagi aku pakai selipar dulu. Tak dan-dan pulak dia. Tak lari pun pasar kau tu.” Aku berjalan menuju ke kereta.
Aku sumbat bagasi ke bahagian belakang kereta. Pintunya tanpa sengaja aku tertutup dengan kuat.
“Weh, tercabut pintu kereta aku. Kau tahu tak kereta ni tunggu masa je nak roboh?” marah Syakila.
Terus aku menghamburkan tawa.
“Tak tercabutnya pintu kereta kau. Aku tak sengajalah. Alahai, dia ni,” ujarku dengan tawa yang masih bersisa.
Risau betul dengan Kancil kesayangan dia.
“Apa pasal kau balik kampung? Cuti lama ke?”
Soalan itu menyapa telinga apabila aku sudah mengambil tempat di sebelah Syakila.
“Lama. Tersangatlah lama. Jomlah ke pasar. Tadi tak menyempat sangat nak pergi.” Aku biarkan saja soalan pertamanya tidak berjawab.
Nanti-nantilah aku bagi jawapan. Lama-lama dia tahu juga.
Syakila menekan pedal minyak, menuju ke pasar pagi. Kami berbual sepanjang jalan. Hati aku kembali resah apabila teringatkan wajah mak.
Alahai, Puan Kalsom, janganlah garang sangat.
AKU mengucapkan terima kasih kepada Syakila. Keretanya berhenti betul-betul di depan rumah aku. Selepas berbicara dalam beberapa minit, dia berlalu pergi.
Syakila dan aku sebaya. Mungkin itu membuatkan kami lebih akrab berbanding sepupu yang lain.
Aku berjalan menuju ke pintu rumah. Aku menghela nafas seketika. Hati rasa begitu berat untuk melangkah masuk ke dalam rumah.
“Assalamualaikum. Mak, orang balik ni.” Aku memberi salam, seraya membuka pintu rumah.
Aku ulang salam beberapa kali sebelum wajah mak menjengah dari dapur.
“Waalaikumussalam. Aik, tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba terpacak dekat rumah aku. Raya pun lambat lagi. Bulan puasa pun belum. Kau salah tengok kalendar ke apa?” Belum apa-apa mak sudah sindir aku.
Aku tersenyum kelat. Rasa dianaktirikan pun ada.
“Makkk... Orang balik bukan nak sambut elok-elok.” Ada nada rajuk di hujung suara aku.
“Alolo, anak bertuah aku dah balik. Meh, mak peluk sikit,” ujar mak sambil tayang wajah penuh ejekan.
Aku sudah tarik muncung mendengar perlian emak. Mak aku memang begitu. Suka perli aku. Aku diam membatu di depan pintu.
Tak lama kemudian, ayah pula muncul dari dapur.
“Eh, ingatkan siapa yang datang. Anak bertuah awak yang balik rupa-rupanya. Dah kenapa diam aje dekat situ? Marilah masuk.” Ayah menggamit aku ke arahnya.
Aku bergerak untuk menyalami tangan ayah. Ayah gosok belakang aku perlahan.
Mak pandang aku macam hendak telan. Aku gagahkan diri hulurkan tangan untuk menyalaminya.
“Kenapa kau balik? Nak duit?” soal mak. Langsung tidak ada kemesraan pada ayat itu.
“Mana ada. Mak ni, ke situ pulak. Bukanlah. Orang saja je nak balik kampung. Tak boleh ke?”
“Lama ke kau cuti? Tadi siapa hantar kau? Mak macam dengar enjin kereta Syakila. Ke mana budak tu?”
“Lama juga. Syakila yang tolong hantarkan. Dah ajak masuk, dia kata ada kerja sikit. Tak tahulah dia nak ke mana. Mana adik-adik?” Aku bersuara dalam kegugupan.
Soal aku berhenti kerja masih lagi aku rahsiakan. Sebolehnya aku tak mahu bercakap soal itu.
“Sekolahlah, mana lagi. Tu pun tak tahu. Nampak sangat tak ambil tahu pasal adik sendiri.”
“Mak...”
“Dah, dah. Mari masuk dulu. Ayah dah beli roti canai. Jom kita makan sama-sama,” ajak ayah.
Ayah tolak aku ke meja makan. Mak sudah tayang muka tak puas hati.
Nasib baik ada ayah yang tolong leraikan kami. Aku gusar kami akan bertegang urat lagi. Mak tu pantang ada peluang. Pasti dia akan kutuk aku kaw-kaw.
Aku dan ayah saling berpandangan. Ayah memberi isyarat supaya aku terus makan. Nampaknya angin mak tak berapa baik hari ini. Walhal sudah empat tahun berlalu. Mak masih marahkan aku.
Aku mengaku, memang aku salah. Tapi, nenek pun tak cakap apa-apa. Mak saja yang lebih-lebih.
“Makan aje, tak payah pedulikan aku,” ujar mak selamba.
Aku carik-carikkan roti canai ke saiz yang lebih kecil. Aku suap roti canai perlahan-lahan ke dalam mulut. Pandangan mata mak sebentar tadi membuatkan aku sukar untuk menelan makanan.
Ayah senyum saja.
Ayah memang terlalu santai. Sebab itu aku lagi suka kalau berbicara dengan ayah. Tapi, kadang-kadang ayah dengan mak sama naik juga. Dua-dua buat aku pening.