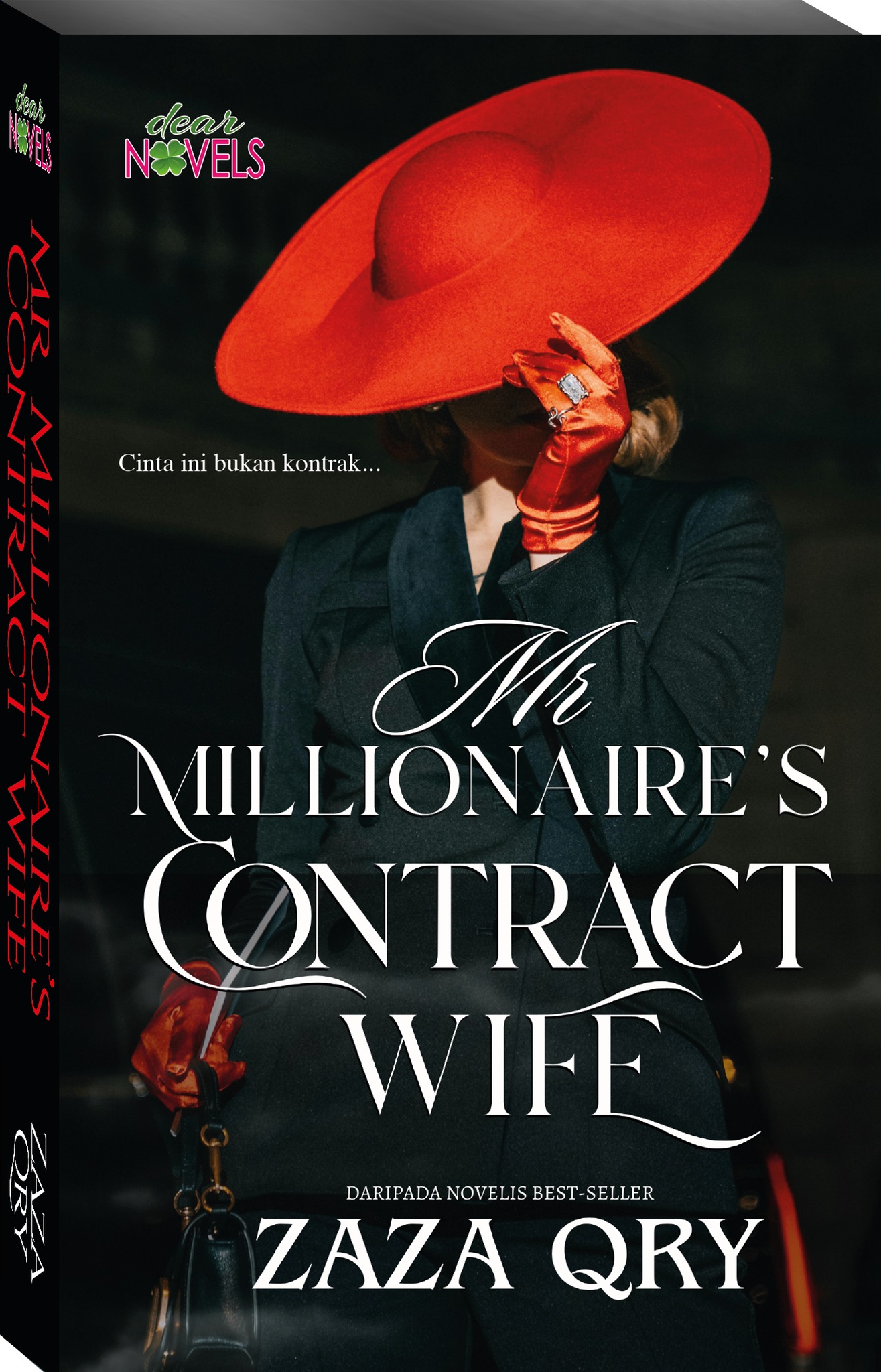FAHMITA duduk di atas tangga rumah separuh kayu dan separuh batu itu.
Sejak beberapa hari yang lalu, dia banyak mendiamkan diri. Ayah kesayangannya sudah meninggal dunia.
Selepas kembali daripada berjumpa seseorang di kota metropolitan itu, kesihatan ayahnya yang sudah merosot jadi semakin merosot. Bukannya dia tak tahu, sejak berpuluh tahun yang lalu, ayahnya masih bersedih kerana ditinggalkan isteri.
Lelaki dengan hati yang lembut seperti ayahnya tentu sangat terasa akibat ditinggalkan.
Selain daripada itu, Fahmita tengah sakit hati kerana kawannya itu sanggup mengkhianatinya. Rumah yang disewa mereka, dia sudah selesaikan dengan tuan rumah. Dia kembali ke bumi Thailand untuk uruskan kematian ayahnya.
Selepas selesai, dia kembali ke Kedah semula untuk bekerja. Disebabkan dia kembali ke Thailand selama seminggu selepas kematian ayahnya itu, dia dibuang kerja. Dia rasa dikhianati oleh majikannya, padahal dia menguruskan kematian ayahnya.
Lagi menyedihkan apabila dia kembali dari Thailand, segala barang-barangnya berada di luar rumah. Lagi menyakitkan, barang-barang rumah yang dibelinya itu sudah masuk ke dalam lori sampah.
Sudah jatuh, tapi ditimpa tangga pula. Tak guna punya kawan.
Dia terus menghubungi Erna, tapi panggilannya tidak berjawab. Nombor telefon Erna sudah tidak digunakan lagi. Nampaknya Erna sudah lama merancangnya.
Fahmita mengeluh perlahan. Dia memang ada masalah dalam kehidupannya. Tapi, dia bukanlah jenis yang menyusahkan orang.
Dia memandang sekeliling kawasan rumah Mek Shun. Lebih kurang sama saja dengan kawasan kampung di Kedah. Bezanya ada lautan di depan mereka.
Mahu tinggal di sini, rasanya dia sudah tak sesuai tinggal di tanah air arwah ayahnya ini. Lagipun dia tak mahu menyusahkan ibu saudaranya itu.
“Fa, jangan bersedih sangat. Arwah ayah tentu tak mahu Fa sedih.”
Suara lembut yang bersuara di belakangnya mengejutkan Fahmita. Sejak tadi dia hanya memandang ke kawasan laut luas di hadapan rumah. Dari jauh dia nampak ada pengunjung di gigi pantai itu.
Pantai yang sentiasa menjadi pilihan pengunjung di sini ataupun orang luar.
“Kalaulah ayah tak pergi, tentu kesihatan ayah takkan terus merosot. Fa dah cakap jangan pergi. Orang dah buang kita, buat apa nak pergi lagi.” Fahmita meraup muka.
Bagaikan mahu memutar semula waktu untuk memujuk ayahnya supaya tidak pergi ke sana.
“Allah SWT dah tetapkan bila ayah nak pergi. Tu cuma asbab saja.” Ibu saudaranya memujuk.
Dia mengusap bahu Fahmita.
“Tapi, dia penyebabnya.” Fahmita masih menyalahkan wanita yang telah melahirkannya.
“Dia tetap ibu Fa,” sampuk Mek Shun.
Fahmita ketawa sinis. Kalau sudah namanya ibu, mana mungkin akan meninggalkannya begitu saja. Kerana kemiskinan?
Ramai saja orang miskin, tapi semua orang tak pernah melarikan diri. Fahmita rasa benci kepada ibunya sendiri.
Mek Shun tersenyum kelat. Sedih mendengar Fahmita membenci ibu sendiri. Kebencian itu muncul kerana ditinggalkan begitu saja, tanpa penjelasan.
“Malaslah nak cakap lagi, mek.” Fahmita mengukir senyuman kelat.
Mek Shun adalah satu-satunya saudara sebelah ayahnya. Adik kepada ayahnya. Dengan Mek Shunlah dia menumpang kasih sayang seorang ibu.
“Fa tak nak jalan-jalan sini dulu ke? Dah lama Fa tak balik sini.” Mek Shun bertanya sambil tersenyum kepada Fahmita yang memandangnya.
“Naklah. Rindu betul dengan tempat ni.” Fahmita sengih lagi.
Phuket memang dikenali dengan pantai-pantai yang cantik. Rugilah kalau dia tak melawat tempat tumpah darah ayahnya.
“Fa nak jumpa Achara dulu.” Fahmita memberitahu.
Sudah hampir setahun dia tidak bertemu dengan Achara. Kawan baiknya itu mempunyai salun rambut berdekatan dengan pantai.
“Mek pun dah lama tak jumpa Achara sejak dia ke sana.” Mek Shun juga memberitahu.
“Mek nak ikut Fa?” tanya Fahmita.
“Tak naklah. Malas nak naik motor jauh-jauh.” Mek Shun menggeleng sambil memandang motosikal Fahmita.
Fahmita menyengih. Meknya itu sudah pasti tak selesa kalau menjadi pembonceng.
Fahmita bingkas dan segera bergerak ke dalam rumah. Tak lama selepas itu, dia keluar semula. Sudah lengkap berpakaian.
“Baju tu kalau tak pakai tak boleh ke?” tanya Mek Shun.
Lemas tengok badan langsing Fahmita dibaluti pakaian ketat.
“Kenalah, mek. Ni baju keselamatan. Naik motor macam ni kena pakai begini.” Fahmita ketawa kecil.
“Ketat macam tu, Mek tengok pun lemas.” Mek Shun membebel.
Fahmita menyengih sebelum menyalami tangan Mek Shun dan dia bergerak ke arah motosikalnya. Helmet disarung ke kepala. Menderum bunyi motosikalnya apabila enjin dihidupkan.
Mek Shun sebenarnya tak suka Fahmita menunggang motosikal berkuasa tinggi macam itu. Tapi, dia nak marah macam mana bila Fahmita tak tinggal sekali dengannya. Balik ke sini pun kadang-kadang saja. Cuma, kali ini dia tinggal lama di sini. Sudah sebulan.
“Jual ajelah motor ni. Mek risau betul tengok Fa bawa motor ni,” omel Mek Shun lagi.
“Tak sampai masanya lagi...” Fahmita menyengih kepada Mek Shun.
“Bawa motor tu perlahan sikit, Fa...” Mek Shun berpesan.
“Insya-Allah, mek. Tapi, motor ni tak sedap kalau naik perlahan...” Fahmita ketawa dengan gurauannya.
Mek Shun menampar bahu Fahmita.
Fahmita menyalami tangan Mek Shun dan terus memecut. Tak sabar mahu berjumpa dengan Achara.
FAHMITA menongkatkan motosikalnya di tempat letak motosikal. Dia menanggalkan helmet dari kepala dan disauk ke lengan. Sebenarnya di sini kebanyakan penunggang jarang memakai helmet, tapi sebab dia sudah lama tinggal di Malaysia, dia sudah terbiasa dengan undang-undang.
Fahmita berjalan melalui kedai-kedai yang dipenuhi pelanggan. Ada pelbagai jenis jualan. Walaupun berdarah Siam, dia bagaikan pelancong saja kerana tidak kerap kembali ke bumi ini.
Pintu salun Achara ditolak. Bunyi loceng membuatkan Achara yang sedang memotong rambut, memandang. Dia menjerit kemudiannya.
“Fa!!” Fahmita menyengih di depan pintu.
“Chan khidtheng ther!” Achara menjerit dalam bahasa Thai.
Tak tunggu lama, Achara terus berlari ke arah Fahmita, memeluknya. Pipi Fahmita terus dicium.
“Lama gila kita tak jumpa,” kata Achara.
“Aku sibuk.” Fahmita menjawab perlahan.
“Kau balik sini buat apa?” tanya Achara.
Dia melihat Fahmita menanggalkan jaket dan meletak jaket itu di atas helmet.
“Aku nak minta maaf sebab tak beritahu kau lebih awal. Ayah aku dah meninggal.” Fahmita mem-beritahu. Matanya berkaca.
“Kenapa?” tanya Achara mengusap lengan Fahmita.
“Dia sakit, ditambah pula terluka dengan apa yang bekas isteri dia buat kat dia. Sebelum meninggal, dia pernah pergi jumpa ibu aku tu. Tak tahulah kenapa dia perlu jumpa dengan ibu aku tu.” Fahmita mencebik.
“Habis tu, macam mana sekarang? Kau nak balik tinggal sini?” tanya Achara.
Kalau Fahmita mahu tinggal di sini, dia lebih gembira.
“Aku boleh hidup sendirilah. Aku takkan terhegeh-hegeh pada perempuan yang dah buang aku.” Fahmita mengetap gigi.
Mungkin dialah anak pertama dalam dunia yang mendendami ibu sendiri.
“Baliklah tinggal sini.” Achara menyuruh Fahmita kembali ke sini.
“Tak mahulah aku. Aku selesa kat sana.” Fahmita menggeleng.
“Kalau kau tinggal kat sini, akulah yang paling gembira.” Achara menyengih.
“Kau guntinglah rambut tu. Kesian pelanggan kau tu. Dah tak senang duduk.” Fahmita muncungkan mulutnya ke arah pelanggan lelaki itu.
Achara meneruskan kerjanya. Dia cekap menggunting rambut pelanggannya walaupun sedang berbual dengannya.
“Kau tutup kedai pukul berapa?” tanya Fahmita.
“Aku boleh aje keluar. Pekerja aku ada.” Achara kenyit mata.
“Aku tunggu kau. Dah lama aku tak ambil angin kat sini. Agaknya aku pun dah lupa jalan,” kata Fahmita sambil ketawa kecil.
“Kau tu lupa daratan.” Achara tergelak-gelak.
Fahmita ketawa sambil memandang cermin. Pelanggan Achara sedang memandangnya. Dia hanya senyum nipis.
Rambut panjangnya yang beralun diselitkan di belakang cuping telinga. Dia memandang sekeliling salun yang luas. Penuh dengan pelanggan dalam kalangan orang asing.
Apa nak hairan? Pelancong yang datang terlalu ramai. Sampaikan ada yang tak mahu pulang ke tempat masing-masing. Entah apa yang menarik sangat tak tahulah.
Ada ladyboy? Atau terlalu mudah nak dapatkan perempuan tempatan? Tak dinafikan, ada juga rakyat asing yang menjalankan perniagaan pelacuran. Fahmita rasa itu adalah antara faktor mudah men-dapat wang.
“Nanti kita cari baju. Aku rimas pula pakai baju ni setiap masa. Tak kena dengan tempat pula.” Fahmita bingkas apabila Achara sudah selesai memotong rambut pelanggannya.
Fahmita pandang dirinya. Lengkap berpakaian sebagai penunggang motosikal.
“Aku ada baju,” kata Achara. Menyengih.
“Baju kau yang tak cukup kain tu?” Fahmita menjuih.
Achara ketawa. Terpaksalah pakai seksi sebab nak tarik pelanggan. Saingannya sengit, ditambah dengan ladyboy yang nyata macam perempuan, berbeza apabila bersuara saja.
Fahmita memilih dress labuh berwarna olive green. Baju daripada kain cotton itu lebih sesuai kerana dia berada di tepian pantai.
“Nampaklah perempuan sikit daripada tadi. Kau ni macam lelaki kalau naik motor tu.” Achara membebel.
“Dari dulu lagi aku minat. Tapi itulah, mek aku tak suka. Tengoklah macam mana nanti. Aku jual aje kut.” Fahmita sengih.
Mungkin dia patut jual saja motosikalnya. Bukan tak sayang, tapi mungkin sudah sampai masanya dia tidak menunggang motosikal berkuasa tinggi lagi. Arwah ayahnya sudah tiada.
“Kau kalau balik sini mesti orang ingat orang sini.” Achara berkata lagi, memeluk lengan Fahmita.
“Aku orang sini. Ayah aku orang sini. Bezanya aku lahir kat sana.” Fahmita menolak bahu Achara.
Dia tetap tak lupa sebahagian daripada dirinya berdarah Siam. Dia tak pernah menidakkannya. Cuma, untuk tinggal di sini, dia tak betah. Dia lebih selesa tinggal di Malaysia.
“Kau masih tunggu Jaffar ke?” tanya Achara.
Fahmita memang ada bercerita pasal kekasih hatinya itu.
“Aku dah janji, kan?” Keningnya terjongket.
“Ya, tak boleh mungkir janji.” Achara ketawa.
“Nanti bila nak kahwin, kau jemputlah aku…” Achara berkata lagi.
“Mestilah. Kau orang pertama yang aku beritahu.” Fahmita ketawa juga.
“Kau memang setia kan?” Achara bertanya.
“Nak bercinta hanya sekali dan berkahwin pun hanya sekali.” Fahmita ketawa dengan falsafah sendiri.
“Kalau aku, tak tahan LDR macam ni. Aku kena jumpa selalu.”
“Itu pun kau tak bertahan juga, kan?” Fahmita ketawa.
Disambut ketawa Achara.