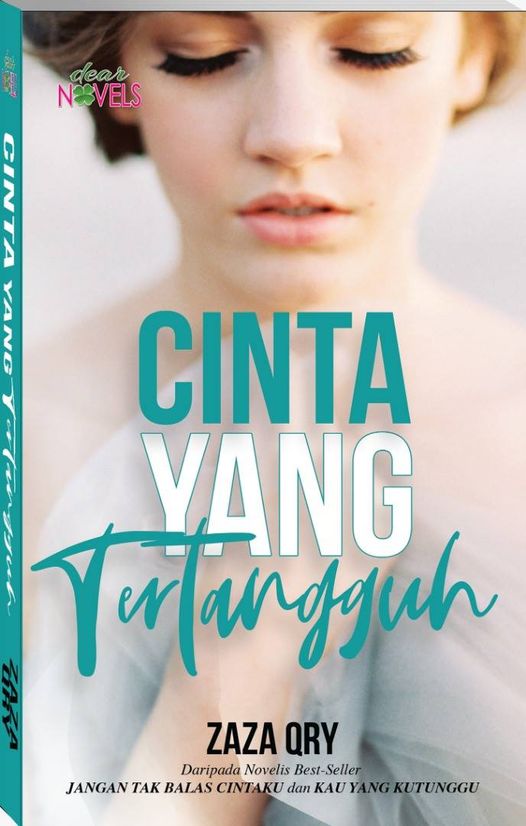ARASH memegang pintu keretanya. Dia memandang ke arah sebuah rumah agam. Dia telah membesar di situ. Pandangannya dihalakan ke arah wanita yang berada di sisinya. Wanita itu mempamerkan wajah tidak senang.
Sungguh dia takut mahu menghadapi apa saja yang bakal berlaku sekejap lagi. Bukan sekali dua dia datang ke rumah ini merayu supaya perkahwinan mereka diterima. Namun, semuanya hampa. Ia tetap ditolak.
“Berjaya atau tak kita kali ni, abang?” tanya Hanani.
“Kita cuba lagi. Kalau tidak berjaya juga, cukuplah sekali ini sahaja. Nani bersama abang kan?” tanya Arash kepada isteri kesayangannya.
“Abang ni pelik. Kalau Nani tak bersama abang, siapa pula yang nak bersama aban?. Ini masalah kita bersama. Kita bukan baru kenal. Dah lama. Lepas tu kahwin pula.”
Hanani senyum sambil meletakkan tangannya di pipi suaminya. Arash menyentuh belakang tangan isterinya dan menciumnya.
“Rumah siapa ni kak?” tanya satu suara kecil di belakang kereta.
Mereka menoleh. Hampir terlupa pada suara kecil yang bertanya itu.
Hanani tidak pernah meninggalkan adiknya itu sejak ibunya meninggal dunia. Sekarang, dialah ibu kepada si kecil itu. Si kecil yang sudah memasuki sekolah rendah.
“Rumah keluarga Abang Rash. Nia tak pernah datang lagi ke sini.”
Hanani senyum kepada adiknya.
“Wah! Besarnya.”
Hanania memandang rumah itu. Dia terpegun melihat rumah yang besar itu. Bukan setakat besar, malah sejak tadi Hanania ralit memandang keliling rumah itu yang mempunyai sebuah taman dan juga sebuah kolam mandi.
Dalam hati kecilnya ada harapan. Alangkah bagusnya kalau dia dapat mandi di kolam tersebut. Tak adalah setiap minggu Abang Rashnya membawa mereka ke kolam renang awam.
“Nia tunggu dalam kereta ya,” arah Arash.
Dia pandang Hanania.
“Baik, Abang Rash.”
Hanania memang adik yang mengikut kata.
Kedua-duanya melangkah masuk ke dalam rumah besar itu. Belum pun sempat mereka sampai ke pintu depan, seorang lelaki yang kemas pakaiannya keluar. Wajahnya bengis yang amat.
“Berani kau berdua datang lagi ke sini!” jerkahnya.
Matanya mencerlung ke arah mereka berdua sambil bercekak pinggang.
“Papa, Rash mohon papa terimalah perkahwinan kami. Rash tak minta lebih daripada itu pun. Cukuplah papa terima kami anak-beranak. Rash takkan tuntut apa-apa pun,” rayu Arash buat sekian kalinya.
Dia tidak jemu-jemu merayu sejak dulu. Dia cuma mahukan restu papanya saja.
“Kau ingat senang aku nak terima anak yatim piatu macam isteri kau ni jadi menantu aku? Aku dah rancang segalanya untuk kau. Anak Tengku Adil kau lepaskan, kau nak aku terima perempuan miskin ni? Jangan harap!” jeritnya lagi.
Matanya mencerlung memandang Hanani.
Hanani diam saja dengan maki hamun bapa mentuanya. Dia sudah lali sejak kali pertama dia datang ke sini. Cumanya, dia tidak berani bertentang mata dengan ayah mentuanya itu.
“Papa, apa kurangnya Nani? Dia lebih baik daripada anak Tengku Adil. Kenapa ayah nampak kebaikan mereka, tetapi tidak nampak kebaikan Nani?”
Arash membela Hanani.
“Aku dah cakap banyak kali. Kau pun dah tahu sebab apa kan. Jangan sesekali jejakkan kaki ke sini lagi!” jeritnya lagi.
“Papa, jangan buang Rash dan keluarga Rash macam ni, papa.” Arash merayu lagi.
Jika boleh, dia mahu ayahnya itu menerima mereka sekeluarga tanpa sikap prejudis. Kalaupun diterima, dia tidak akan pulang dan tinggal di sini.
“Kau dengar sini, Rash. Mulai saat ini, kau bukan lagi anak aku. Anak aku hanyalah Adrish seorang. Kau! Aku keluarkan kau daripada senarai wasiat aku. Nyah kau dari sini!” kata Encik Reza.
“Papa! Jangan buat macam ni. Rash tetap anak papa. Rash tak perlukan harta papa. Rash hanya nak jadi anak papa saja,” kata Arash lagi.
“Hei! Kau ni tak faham ke? Ayah kau dah putuskan hubungan dengan kau! Keluarlah. Hei, perempuan! Bawa suami kau keluar dari sini!”
Seorang perempuan bergaya menghalau Arash dan Hanani. Perempuan itu tak lain tak bukan adalah ibu kepada anak kedua Encik Reza, Tengku Raziah.
“Mama, jangan macam ni mama,” kata Arash.
Arash tidak kisah dengan harta papanya, tetapi dia tidak sanggup apabila Encik Reza mahu memutuskan hubungan dengannya.
“Kenapa? Kau takut merempat? Kalau macam tu, tinggalkan perempuan ini dan kembali kepada anak saudara mama.”
Tengku Raziah memberi kata putus.
“Mama,” panggil Hanani lembut.
Tak sangka ibu mentuanya itu sanggup memberi syarat sebegitu rupa.
“Diam! Mulut kau tak layak panggil aku mama! Dasar perempuan tak sedar diri!” jerkahnya.
Tangannya menolak tubuh Hanani. Hanani jatuh terjelepok di sisi Arash.
Dalam kereta, Hanania menjadi pemerhati. Bagi seorang budak perempuan yang masih kecil, dia tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dia membuka pintu kereta perlahan-lahan.
Dia mahu melihat lebih dekat apa sebenarnya yang berlaku. Dia nampak perempuan bergaya itu menolak kakaknya. Dia melangkah perlahan-lahan ke dalam kawasan rumah itu. Dia mahu menghampiri kakak kesayangannya.
Belum pun sempat dia mahu melangkah masuk, tangan kecilnya ditarik. Dia memandang. Kelihatan seorang budak lelaki sedang memegang tangannya.
“Hah! Abang ni sapa?” tanya Hanania terkejut.
Dia ketakutan. Dia mahu menjerit, tapi budak lelaki itu sempat memekup mulutnya. Hanania tahu lelaki itu lebih tua daripadanya. Budak lelaki yang sedang memegang tangannya terlalu tinggi. Hanania terpaksa mendongak untuk melihat wajahnya.
“Jangan pergi! Mereka tengah bergaduh,” beritahunya.
Dia senyum kepada Hanania.
“Saya nak pergi kepada kakak saya,” kata Hanania sambil memandang kakaknya yang masih lagi belum bangun akibat tolakan perempuan tadi.
“Jangan! Mereka tengah bergaduh tu. Tak payah dengar apa yang mereka nak cakap.”
Budak lelaki itu menegahnya sekali lagi.
“Saya nak tolong kakak dan Abang Rash.” Hanania meronta. Mahu melepaskan tangannya daripada terus dipegang oleh budak lelaki tinggi lampai itu.
“Tak boleh! Budak kecik mana boleh dengar orang maki hamun. Tak baik untuk telinga ni,” kata budak lelaki itu sambil mencuit telinga kecil Hanania.
Hanania memekup sebelah kiri telinganya dengan tangan kiri. Budak lelaki itu senyum.
“Lepaslah, saya tak kenal abang pun.” Hanania meronta lagi.
“Saya tinggal dalam rumah ni juga,” beritahunya.
“Lepaslah.” Muka Hanania sudah mencebik. Dia mahu menangis.
Hanania meronta lagi. Rontaannya kali ini lebih kuat, menyebabkan rantai tangan silver kecil yang berada di tangannya terputus. Hanania berlari ke arah kakak dan Abang Rashnya yang sedang berjalan ke arahnya.
Mereka bertiga melepasi budak lelaki tadi. Pandangan budak lelaki tersebut berpadu dengan pandangan Arash. Arash tidak berkata apa-apa, cuma menghantar pandangan yang sukar dimengertikan.
Budak lelaki tersebut memandang Arash dan isterinya dan juga budak perempuan kecil yang ditarik tangannya oleh Hanani.
Dia tidak mampu menahan abangnya daripada pergi. Dia tahu sejak mamanya berkahwin dengan papa mereka, Arash tidak pernah menegurnya. Entah kenapa abangnya itu payah sekali hendak menegurnya. Padahal mereka berkongsi papa yang sama.
Sekali lagi pandangannya jatuh kepada budak perempuan yang rambutnya berekor kuda itu. Dia tidak sempat mengembalikan rantai tangan silver itu. Dia menggenggamnya kuat. Sesungguhnya dia tidak mahu perkara seperti ini terjadi. Dia tidak dahagakan harta, tapi cukuplah abangnya itu menerimanya.
Tapi, papa sudah memutuskan hubungan dengan abangnya. Dia hanya memandang. Apalah yang boleh dilakukan oleh budak sekolah menengah sepertinya. Lambat-lambat dia melangkah ke arah mamanya.
“Rish, bila sampai dari sekolah?” tanya mamanya.
“Baru aje,” jawabnya.
Malas nak cakap dia sebenarnya tahu apa yang berlaku tadi.
“Baguslah kalau baru sampai,” kata mamanya.
Mamanya menarik tangannya dan mereka melangkah masuk ke dalam rumah.
Adrish pandang wajah ayahnya yang memerah. Mungkin kerana masih ada lagi sisa-sisa kemarahan terhadap abangnya.
“Papa, tak boleh ke…”
Belum pun sempat dia menghabiskan ayatnya itu, mamanya mencubit lengannya. Dia memandang mamanya dengan pandangan pelik. Dia sudah tidak boleh bersuarakah?
Tengku Raziah menarik tangan anak tunggalnya pergi dari situ. Adrish hanya mengikut saja ke mana mamanya itu mahu membawanya.
“Kenapa mama bawa Rish ke sini? Rish nak cakap dengan papa. Salah apa yang papa lakukan. Anak papa hanya kami berdua saja. Tak baik apa yang papa buat kepada Abang Rash.”
Adrish pandang mamanya.
“Aisy, jangan masuk campur hal papa,” kata Tengku Raziah lagi.
“Bukan masuk campur, mama. Hal Abang Rash, hal kita juga. Dia abang Rish,” sambung Adrish lagi.
Dia tidak puas hati dengan kata-kata mamanya. Mana mungkin itu cuma hal papa, sedangkan anak yang dihalau itu juga adalah anaknya. Dia juga anak papa.
“Mama tak nak Rish masuk campur hal Arash. Arash pun bukannya boleh terima Rish sebagai adiknya,” kata Tengku Raziah selamba.
Tengku Raziah lega kerana Arash sudah dihalau. Sekurang-kurangnya, segala harta mereka akan menjadi milik Adrish seorang.
“Kalau Rish pun tak boleh terima, mama, kalau tiba-tiba satu hari papa bawa balik seorang lagi adik. Sedangkan selama ini kita tak tahu akan kewujudannya pun. Pula tu pada hari kematian ibu sendiri. Kalau mama, boleh terima ke? Mama tak rasa mama sudah merampas? Merampas kehidupan seorang wanita. Rish tahu, mama. Ibu tiri Rish tu tahu kewujudan mama,” kata Adrish lagi.
Dia tahu secara tidak sengaja.
“Diamlah. Mama tak suka Rish ungkit hal lama tu. Mama tak nak dengar lagi,” kata Tengku Raziah.
Dia sedar dia telah menggunakan muslihat untuk memiliki suaminya ini, tapi itu bukannya salah dia seorang. Suaminya juga turut bersalah. Tergoda dengan dirinya, kenapa?
Adrish terus melangkah naik ke atas. Dia mahu berehat. Rantai tangan kecil itu dilempar ke dalam laci. Mahu membuangnya, tetapi dilihat rantai tangan itu masih cantik lagi. Biarpun dia tahu dia tidak akan bertemu dengan pemiliknya lagi.