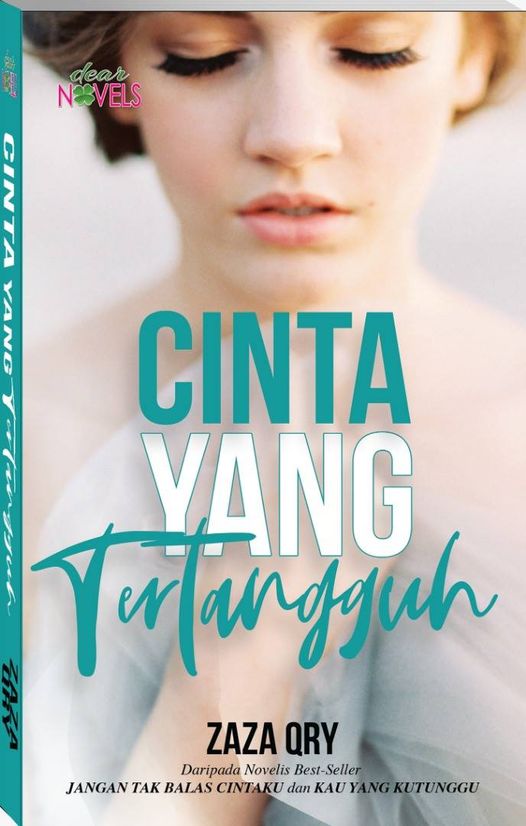HANANI memandang suaminya yang duduk di meja kerjanya. Sejak tadi suaminya itu membelek-belek kertas putih yang bertulis itu. Hanani menghampirinya. Bahu Arash diramasnya perlahan.
“Sedapnya bila Nani urut,” kata Arash sambil menutup kertas putih tadi dengan tangannya.
Dia memusingkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Hanani meramas lagi kedua-dua belah bahu Arash.
“Abang ada masalah ke?” tanya Hanani.
Dia tahu bila Arash ada masalah atau tidak. Sudah lama mereka hidup bersama. Segala jenis perangai suaminya, dia sudah tahu.
“Tak adalah. Kenapa Nani tanya?” tanyanya perlahan.
Arash juga tahu mana mungkin dia boleh menyembunyikan sesuatu daripada pengetahuan isterinya.
“Nani bukannya sehari kenal abang. Kita kenal sejak dari sekolah lagi,” kata Hanani, tunduk mencium pipi Arash.
“Abang tahu Abang cuba juga yang nak sembunyikan perkara ni daripada Nani. Mana tahu kali ni berjaya,” ujar Arash tergelak kecil.
Hanani menampar bahu suaminya perlahan. Dia menarik kerusi lalu duduk di sisi suaminya. Matanya merenung mata Arash.
“Ceritalah. I’m a good listener,” kata Hanania sambil menarik jemari suaminya lalu menggenggamnya.
“Bahri, dia larikan duit projek. Abang pening kepala dengan hal ni. Abang tak tahu dia di mana sekarang. Itu bukannya satu-satunya masalah yang dia timbulkan. Rupa-rupanya semasa dia mahu menjadi rakan kongsi abang, dia pinjam duit dengan along. Dah tu, dia tak bayar hutang,” cerita Arash setelah lama menyembunyikan masalahnya.
“Ya Allah, kenapa dia sanggup buat macam tu?” Hanani menutup mulutnya.
“Habis tu, sekarang macam mana?” tanya Hanani lagi.
“Abang pun buntu sekarang ni. Mana tahu dia akan buat onar kat abang. Abang kenal dia sejak dari universiti lagi. Abang dah pergi rumah dia. Tapi, dia dan keluarganya dah menghilangkan diri,” beritahunya lagi.
“Tapi, along tu tak cari abang kan?”
Hanani mula merasakan ada sesuatu yang lebih besar berlaku.
“Dah datang pun. Bahri letak nama abang sebagai penjamin.”
Arash tunduk. Dia sakit hati dengan apa yang berlaku. Dia tak mahu along itu datang mengganggu ahli keluarganya.
“Astaghfirullah al-azim. Habis tu, macam mana ni?” Hanani bertanya bimbang.
Bukannya dia tak tahu bagaimana perangai orang yang memberi pinjaman itu. Mereka sanggup membunuh.
“Nani jangan risau. Abang dah bayar sikit. Buat masa sekarang, mereka takkan ganggu abang lagi. Cuma apa yang merisaukan abang, projek tu terpaksa dihentikan sementara sebab duit untuk abang beli material tu dah dihabiskan untuk membayar hutang. Tak apa, abang akan cuba cari lagi.”
Arash cuba menenangkan hati isterinya walaupun dia sendiri sudah buntu mahu mencari wang.
“Jangan risaukan budak berdua tu sudah. Nanti kalut pula Nia kalau abang ada masalah. Qer pula, lebih baik dia tidak tahu langsung. Nanti mengganggu pelajaran dia pula,” pesan Arash.
“Nani tahu,” katanya perlahan.
“Abang, sudah-sudahlah fikir pasal ni. Sekarang waktu untuk abang berehat. Kita tidur ya.”
“Hmm.”
Arash menutup lampu meja kerjanya. Dia melangkah bersama dengan Hanani ke katil. Arash tahu dia tidak akan habis berfikir tentang ini. Kerana ada satu perkara lagi yang dia sembunyikan daripada Hanani. Geran rumah ini terpaksa diserahkan kepada along itu sebagai cagaran jika dia tidak dapat membayar hutang Bahri.
Bahri memang kawan yang makan kawan. Sanggup Bahri kenakan dia sampai begini.
AFII menyandar di sisi keretanya. Sejak 15 minit yang lalu dia menanti Hanania. Bukannya Hanania tidak memberitahunya dia akan lewat, tapi dia yang tidak sabar mahu menemui Hanania. Seminggu di luar Kuala Lumpur menyebabkan dia terlalu merindui Hanania.
“Hai, melamun apa ni?”
Tiba-tiba suara orang yang amat dirinduinya itu kedengaran di cuping telinganya. Afii menoleh dengan senyuman lebar. Wajah bersih Hanania dipandang tanpa mahu mengalihkan pandangannya.
“Apa ni? Malulah kalau pandang lama-lama,” tegur Hanania.
Dia menunduk. Memang begitulah Hanania. Tak boleh Afii tenung lama-lama.
“Alah, dah hampir enam tahun lebih kita kenal, awak tetap macam ni. Nak tenung lama-lama pun tak boleh,” kata Afii, menyengih.
“Bukan tak boleh, tapi seganlah awak pandang lama-lama,” balas Hanania.
“Jom kita makan. Laparlah,” ajak Afii.
“Hmm, saya pun dah lapar sangat ni. Tapi, kat mana kita nak makan?” tanya Hanania.
“Kalau ikut hati, nak makan masakan Kak Nani. Tapi, tak ada privasi pula kalau makan kat rumah. Hari ni saya nak berdua-duaan saja dengan awak,” kata Afii sambil membukakan pintu kereta untuk si kekasih hati.
“Nak kira privasi apanya? Ramai-ramai lagi bagus. Syaitan pun lari. Kak Nani okey aje kalau kita suruh dia masak,” kata Hanania.
“Amboi! Macamlah kita ni termakan hasutan syaitan tu. Selama kita kawan, mana pernah saya buat tak senonoh kat awak.” Afii menyangkal.
Itu memang benar. Hanania sentiasa menjaga batasnya sebagai seorang perempuan.
Hanania ketawa besar dengan kata-kata Afii. Memang dia mengaku, Afii tidak seperti lelaki lain yang akan memeluk, mencium pasangan kekasih sesuka hati. Hanania tidak mahu dianggap sebagai perempuan yang murah. Kerana cinta, sanggup buat apa saja.
Tidak, Hanania bukan begitu.
Afii terus memandu keretanya. Mereka berhenti di sebuah restoran. Sengaja Afii memilih restoran yang jauh dari bandar. Senang mengelak daripada matamata gelap yang dihantar oleh ibunya. Afii pun hairan kenapalah sampai begitu sekali ibunya menentang hubungan mereka.
“Makan apa pun kalau dengan awak memang sedap,” kata Afii setelah selesai makan.
“Saya takut ayat awak manis sekarang aje. Nanti bila lepas kahwin, dah tak macam ni. Nak makan kat luar mesti seorang diri. Bawa bini buat menyemak aje,” kata Hanania.
Dia mencebik sedikit.
“Awak kena yakin, Nia. Saya akan tetap macam ni walaupun sudah berkahwin dengan awak.”
Afii yakin dengan kata-katanya. Dia akan melayan Hanania lebih baik selepas berkahwin.
Hanania senyum. Entah kenapa dia tidak gembira dengan kata-kata Afii. Afii pula perasan ekspresi wajah Hanania berubah.
“Awak jangan sedih. Ibu pasti akan terima hubungan cinta kita. Saya tengah pujuk dia,” beritahu Afii.
Dia memang sedang memujuk ibunya supaya menerima Hanania. Dia hairan kenapa ibunya masih mementingkan darjat. Zaman moden macam ni, patutnya segala jenis darjat itu sudah ditolak ke tepi.
“Entahlah, Afii. Saya tak mahulah kerana hal kita, awak dan ibu awak bergaduh pula nanti. Saya tak mahu awak jadi anak derhaka.”
Hanania menunduk.
“Jangan fikirkan lagi. Yang penting sekarang, kita bahagia kan,” pujuk Afii.
Dia senyum kepada Hanania. Hanania mengangguk. Dia tersenyum manis semula. Moga hubungan cinta mereka akan direstui oleh ibu Afii.
Telefon yang berbunyi dari dalam beg tangan Hanania membuatkan tumpuan mereka berada di situ.
“Kak.” Dalam senyuman, Hanania menyebut.
Namun, bukan suara percakapan yang kedengaran, tetapi esakan kakaknya. Jantungnya tibatiba berdegup kencang.
“Kak, kenapa ni, kak? Kenapa kakak menangis ni?” tanya Hanania.
Hanania semakin risau. Esakan masih lagi kedengaran.
“Kak! Kenapa ni kak? Ada sesuatu berlaku pada Mya atau Qer ke?”
“Nia… abang… Abang Rash, Nia.”
Terhenti-henti cakap kakaknya. Hanani masih lagi menangis.
“Kenapa dengan Abang Rash, kak?” tanya Hanania.
“Dia kemalangan di tempat kerja. Abang Rash dah tak ada.”
“Allahuakbar, Abang Rash.”
Telefon yang dipegang Hanania melurut jatuh ke bawah. Afii cepat-cepat menyambut telefon itu daripada menyembah lantai.
Hanania tiba-tiba gelap mata. Dia tidak ingat apaapa lagi. Apa yang dia ingat, Afii menjerit memanggil namanya.